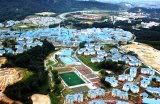Mungkin benar berita-berita menyedihkan tentang Tanah Air kita, Indonesia. Negara yang super korup, banyak kriminalitas, belum dengan kemacetan yang luar biasa, hingga hiruk-pikuk polemik lainnya. Yah…Indonesia mungkin memang rumit. Rumit dengan segala unsolved problems-nya. Namun tentu, benar kata pepatah bahwa hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri seberang. Indonesia mungkin memang belum sesempurna harapan rakyatnya, namun sebagai bangsa yang nasionalis, tentu kitalah yang harusnya membawa Ibu Pertiwi menuju kesempurnaan itu.
Penulis acap kali termenung kontemplatif memikirkan kasus demi kasus yang terjadi di Indonesia. Ujung-ujungnya, kesimpulan yang didapatu selalu saja sama; bahwa mayoritas masalah Tanah Air berhulu pada sebuah masalah inti berupa ‘penyakit mental bangsa’. Minimnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentang slogan kepentingan sosial di atas kepentingan individual menjadi salah satu momok yang menjiwai hampir seluruh polemik Tanah Air. Tentu, dari yang terkecil hingga yang paling mengerikan.
Melalui blogging ini, penulis ingin sekedar bertutur kata menyampaikan isi hati untuk Ibu Pertiwi. Apa yang penulis lihat sebagai penyakit mental bangsa ini ingin penulis tulis dan ulas sesingkat-singkatnya, namun dengan komposisi sedetail-detailnya. Atau paling tidak, mampu menjadi gambaran pembaca.
Tulisan akan bersambung episode demi episode dengan ulasan kasuistik terhadap masalah-masalah Tanah Air. Jika memungkinkan, akan ada selingan tulisan-tulisan lain yang tak melulu berangkat dari model problema di Indonesia, namun menggunakan sudut pandang lain. Yang pasti, tulisan bersambung ini akan membahas tentang Indonesia, negara Tanah Air penulis yang tercinta. Demi perbaikan ke depan, usaha apapun dapat dilakukan. Sekecil apapun.[Mc-V]

“Terhitung sejak satu Januari 2011 nanti, aturan itu diberlakukan.”
Musibah bagi mereka dan kami-kami yang berada di luar negeri. Pemerintah berjanji akan mulai menetapkan pajak barang bawaan luar negeri. Malam itu, sekali lagi guruku yang mendaku a-nasionalis menjejaliku dengan keburukan-keburukan pemerintah Indonesia. Yah, aku tahu bahwa inisiasi a-nasionalis ini hanya topeng belaka karena kuyakin beliau, guruku ini, memiliki nasionalisme yang jauh lebih tebal dari yang kubanggakan tiap saat.
Kabarnya, menurut guru sekaligus sahabatku ini, bahwa fiskal tak lagi diberlakukan karena pemerintah merasa malu pada negara-negara lain. Lalu, demi menutup kemandegan pajak keluar negeri ini, pemerintah hendak menerapkan –atau tepatnya hendak mengetatkan– pajak barang luar negeri. Mulai awal Januari ini, fiskal akan reinkarnasi menjadi pajak barang luar negeri. Celetuk sobatku tadi, “Harusnya kalau alasannya malu, semenjak dahulu sudah dipugar fiskal itu!”
Indonesia memang aneh. Bukan hanya dalam kasus fiskal ini saja. Dan obrolan kami malam itu membuktikan adanya bejibun keanehan –atau biasa disebut masalah–- yang melekat di tubuh Ibu Pertiwi. Ah….bukan waktunya membahas hal-hal ini. Enggan, pun segan.
Terlepas dari tangan-tangan jahil di sekitarnya, fiskal merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi pemerintah Indonesia. Hanya saja, yang selama ini menjadi masalah adalah generalisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengejawantahkan aturan ini. Bukan hanya Bakrie yang maha kayanya itu yang harus membayar fiskal, namun Sutedjo yang uang tiketnya pun hutang demi mengadu nasib di negeri orang juga harus membayar fiskal. Fakta menunjukkan bahwa desakan penghapusan fiskal lebih gentar dilancarkan oleh mereka yang memang mempertimbangkan pengeluaran hidup. Sedang bagi mereka yang hanya butuh mengedipkan mata untuk mencari ratusan juta rupiah, lebih senang bertutup mulut.
Agaknya, pemerintah memahami dampak ini. Dan seperti pengurangan serta limitisasi BBM, pemerintah pun hendak memberikan subsidi kepada mereka yang membutuhkan agar tidak perlu membayar fiskal. Masalahnya, standarnya sulit, dan mudah di’akali’. Oleh karenanya, penerapan pajak barang luar negeri yang mulai diterapkan awal 2011 ini dapat dikatakan sebagai upaya baru untuk menuntut dana lebih banyak dari orang-orang berduit.
Ketika mereka pulang dari luar negeri membawa banyak barang-barang berharga dari luar negeri, itu artinya mereka memang memilki uang yang lebih dibanding yang lain. Wajar akhirnya jika mereka diharuskan membayar pajak masuknya barang-barang berharga itu. Lagipula, membeli barang produksi di luar negeri berarti mengurangi pendapatan negara, dan tentu para warganya. Sudah menjadi sebuah konsekuensi untuk membayar itu.
Nalar berpikir bangsa Indonesia amat dihegemoni oleh nafsu akan kenikmatan lokal yang amat terbatas. Jika kita menyempatkan diri berdialog pada para petani dan rakyat kecil lain yang kurang peka terhadap kondisi pemerintah secara komperehensif, mereka pasti akan mengumbar ucap bahwa era Pak Harto jauh lebih indah daripada yang ada sekarang. Tentu, kita –kaum akademisi dan pengamat politik– yang melaknat Pak Harto dapat memaklumi kesalah para petani itu.
Laiknya fenomena itu, kemudahan untuk keluar negeri dengan gratis tanpa fiskal atau masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak barang berharga merupakan representasi kebijakan Pak Harto. Sedang keharusan keduanya, atau salah satu saja, menjadi gambaran pemerintah yang lebih bijaksana. Jika kita memagn minim pendidikan dan awam politik, wajar jika kita tak ingin fiskal dan pajak itu diberlakukan. Namun, jika sebaliknya, sudah seharusnya kita mendukungnya.
Bukan hanya dalam polemik fiskal nalar bangsa Indonesia sering sedikit serong dari yang seharusnya. Dan bukan pula penulis mengecualikan dirinya dari bangsa Indonesia pada umumnya, karena penulis juga bangsa Indonesia. Maka, mari kita bayar pajak…….[Mc-V]
Namanya Pusda Sari. Wanita putih paruh baya dari ras Cina itu tak kusangka memiliki nama yang amat mengindonesia. Waktu itu aku bersyukur karena perjalanan udara 2 jamku tak kan membosankan. Sukses di perjalanan darat dua hari lalu, hasratku menuntunku untuk kembali mengulanginya di penerbangan Air Asia ini.
Dari mukaddimah perbincangan kami, aku tahu kalau dia bersama belasan guru gereja lain sedang akan berlibur selama 3 hari di Malaysia. Tentu bukan uang dari kas gereja yang mereka gunakan untuk berlibur ini –karena itu berarti mereka yang agamawan ini tak berbeda dengan Gayus Tambunan. Mereka telah menabung bersama melalui lembaga gereja semenjak dulu hingga terkumpul tabungan itu dan cukup untuk digunakan berlibur.
Awalnya, cukup heran juga. Pusda yang notabene beragama Kristen –bahkan menjadi ustadzah di gereja– terlihat begitu ramah dan renyah bercakap denganku. Lambat laun ia ngaku, bahwa kakek-neneknya beragama Islam. “Pantas saja”, gumamku. Pasangan Islam ini memiliki 15 keturunan, 7 yang pertama –dan salah satunya adalah orang tua Pusda– beragama Kristen, 8 yang terakhir Muslim. Ternyata, kakek-nenek Pusda bukan Muslim sembarangan. Awalnya, selaku Chinese, mereka menganut kepercayaan Budha. Terasimilasi oleh budaya tempat mereka tinggal, agama mereka pun berubah menjadi Kristen Katolik. Belakangan, ketika hijrah ke Lampung dan hidup dikelilingi oleh budaya Islam, mereka pun akhirnya lagi-lagi merubah agamanya. Kali ini, dan semoga yang terakhir, menjadi Islam.
***
Ke-15 putra-putri pasangan itu bernasib sama denganku. Tapi tidak dengan orang tua itu. Tidak dengan pasangan itu. Tidak dengan kakek-nenek Pusda Sari. Sungguh tidak. Mereka benar-benar agamawan. Bagi mereka, Tuhan bukanlah barang warisan yang begitu mudahnya diestafetkan dari generasi ke generasi.
Kala itu, jauh di seberang Eropa sana, para filosof sedang meramu konsep paling kompatibel untuk mendefinisikan agama. Alhasil, serumit atau sesederhana apapun agama itu, tetap saja kan berujung pada sebuah kepercayaan dan keyakinan di dalam jiwa. Berangkat dari fenomena wajib dalam sebuah agama ini, manusia sepakat bahwa jika dikasarkan, maka Tuhan dan agama yang dipimpin-Nya hanyalah merupakan kebutuhan psikologis manusia.
Bagi penulis, keyakinan batiniyyah ini amat subjektif dan individualis. Ini bukan merupakan keyakinan turun-temurun yang dipaksakan oleh nenek luhur keluarga. Bahkan, jika bukan karena ingat agama sendiri, maka mungkin penulis akan menegaskan bahwa sah-sah saja jika setiap individu yang baru eksis ke dunia ini memiliki konsep beribadah dan bersembah pada Sang Maha yang sama sekali berbeda dengan individu-individu lain sebelumnya. Dan ingat, setiap individu. Maka agama bukan lagi menjadi sesuatu yang diseragamkan karena semua percaya dengan pola keberagamaannya sendiri-sendiri.
Akan tetapi, penulis masih yakin, bahwa eksistensi agama-agama yang lalu dianut oleh banyak person merupakan manifestasi kultur manusia yang selalu ingin berjalan di atas jalan yang pasti menuju kebenaran. Manusia, secara natural, tak ingin hidup dalam awang-awang yang tak jelas juntrungnya. Manusia lebih nyaman jika hidup dalam sebuah lintasan spesifik yang telah ditentukan ini itunya agar begini begitu.
Yang menjadi masalah adalah ketika di satu sisi manusia menyadari ada banyak lintasan berbeda menuju hal sama bertajuk ‘orgasme transendental’, di saat yang sama, mayoritas dari mereka enggan dan ragu untuk memilih lintasan yang klop bagi mereka. Sifat minder dan kekurangpercayadirian manusia untuk bertindak sendiri menjadi alasan utama hal ini. Maka akhirnya, kepuasan hubungan intim manusia dengan Tuhan pun terkadang seperti ejakulasi anak-anak orang yang dicabuli dengan paksa oleh para pemerkosa.
Tapi tidak dengan kakek-nenek Pusda. Agaknya mereka tahu benar maksud dari kisah Nabi Ibrahin a.s. Tuhan bukan diberi, namun dicari. Pasangan ini pun mulai mencoba lintasan demi lintasan yang ada untuk akhirnya memantapkan diri memilih Islam sebagai jalur mereka berinteraksi pada Tuhan –atau dalam bahasa filosofis Barat tadi, memuaskan batin diri sendiri.
***
Dewasa ini, klan-klan ideologis semakin berpuspa ragam. Variannya menjamur dari yang paling ekstrim fundamentalnya, hingga paling ekstrim liberalnya. Sayangnya, mereka lupa bahwa mayoritas dari mereka berideologi karena dogma dan doktrin orang tua serta lingkungan sekitarnya, baik langsung maupun tidak.
Penulis tak menyalahkannya. Penulis juga lahir dari peranakan yang sama. Ibu dan Bapak mewariskan kepercayaannya pada penulis. Bahkan, –meminjam bahasa para wartawan– hingga coretan ini dibuat, penulis masih berpikir keras tentang generasi mendatang. “Apakah anakku kelak akan kubebaskan mencari Tuhannya sendiri, ataukah harus kubimbing?” Entah. Yang pasti, Pusda bukan seperti para wanita Muslim yang selalu manja dan jaim hingga dalam urusan cinta yang seharusnya tak mengenal emansipasi pun mereka tak sudi untuk menembak dahulu. Di landasan Air Asia itu, Pusda dengan senyum ramahnya mendahuluiku untuk mengucapkan selamat tinggal. Aduhai ramah mempesonanya wanita ini. Sore pun serasa tak mengenal temaram yang kan menjemputnya.[]
Alkisah, sejarah dimulai ketika tulisan ditemu. Tepatnya 3000 tahun sebelum Masehi, tulisan paku yang dikenal dengan cuneiform menjadi titik mula sejarah manusia dimulai. Sebelum itu, peradaban sederhana manusia dikenal dengan era pra-sejarah. Tulisan menjadi titik mula sejarah dimulai.
Bukti-bukti sejarah digali dengan bantuan prasasti-prasasti kuno. Peradaban manusia dikenal dari informasi-informasi literal yang ada. Bahkan, eksistensi agamapun terrefleksikan oleh kitab-kitab suci. Al-Qur`an, sebuah tulisan, menjadi warisan yang paling bernilai bagi umat Islam. Lagi-lagi, tulisan menjadi simbol peradaban manusia.
Entah sudah berapa ribu buku dan risalah yang dianggit oleh Imam Syafi’i, Ghazali, dan ulama-ulama Islam lainnya. Pun ratusan naskah diwariskan oleh Imam Nawawi al-Bantani, Abd al-Shamad al-Palimbani, Nuruddin al-Raniri, Ihsan al-Jampesi dan ulama Nusantara lainnya. Bukan hanya sebagai bukti eksistensi dan kompetensi intelektual mereka, namun teks-teks ini telah menjadi gudang ilmu pengetahuan dunia. Kali ini, tulisan malah menjelma menjadi titik sentral peradaban dan ilmu pengetahuan.
Dus, menulis menjadi tradisi yang bukan lagi harus, namun pasti diwariskan dan dibudidayakan. Maka semangat produktivitas akademik pendahulu dalam tulis-menulis ini, sudah selayaknya dimiliki oleh akademisi kontemporer. Tak terkecuali santri, yang pada hakikatnya, merupakan lokomotif akademik dalam dunia keislaman. Basis pengetahuan Islam dimulai dari sini.
Dalam tulisan ini, penulis ingin sedikit menggelitik nalar dan emosi santri agar produktif menulis, dan terlebih, mampu merepresentasikan gelombang intelektual Islam melalui coretan-coretannya. Hanya dua poin yang hendak penulis sampaikan.
Pertama, apa yang didapat dari menulis? Pertanyaan ini menjadi (semacam) legalisasi paling umum bagi mereka yang enggan menulis. Untuk apa membuang lelah demi sesuatu yang tak jelas, katanya.
Niscaya lumrah jika berbilang bahwa dia, dia, dan dia rajin bekerja. Pekerjaannya menelurkan uang. Terbentuk profit materil dari aksi ini. Di sisi lain, ternyata, si dia, dia, dan dia yang lain, rajin sekali berpacaran (baca: ta’aruf). Terhasil efek kepuasan psikologi dari prosesi itu.
Berangkat dari fenomena ini, maka iming-iming fisik maupun batin harusnya mampu menjadi pelecut utama agar gemar menulis. Seperti halnya orang bekerja yang akan mendapatkan gajinya, orang yang menulis juga dibayar. Namun layaknya, perkara yang terlalu material-duniawi ini tak disebut. Ia akan menjadi tema tersendiri dalam dunia tulis-menulis yang lebih lanjut. Lain halnya dengan kepuasan batin yang akan didapat sejak pertama kali mencoretkan pena ke selembar kertas. Seperti halnya seorang lelaki yang rajin apel ke rumah doi, dia akan mendapatkan kepuasan batin dari pacarannya itu. Maka mereka yang menulis pun, akan mendapati kepuasan batin dari tulisannya.
Mengandaikan sebuah contoh, ketika tulisan si Fulan dimuat dalam buletin lokal pondok pesantrennya, rekan-rekanita si Fulan akan menengarai tulisannya. Terlepas dari efek lanjutan apakah si Fulan akan membusungkan dada ketika berjalan, atau justru merona tersipu malu, namun haqiqatan, si Fulan pastilah merasakan kebanggan tersendiri. Namanya dikenal sebagai seorang kontributor buletin. Sebagai sosok yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menulis. Tidak hanya dalam buletin, namun dalam semua media, termasuk yang bersifat personil, seperti notes di Facebook atau blog. Kebanggaan muncul ketika banyak komentar masuk, kritik maupun apresiasi.
Idealnya, motif menulis bukanlah keuntungan belaka, namun lebih karena tanggung jawab sosial-akademik. Namun, seperti halnya ibadah, menulis juga memiliki tahapan-tahapan keikhlasan. Penulis teringat pada konsep ‘ubudiyyah yang dimunculkan oleh para Sufi. Dalam ‘Ushfuriyyah pun dijelaskan bahwa keikhlasan seseorang beribadah dapat dikategorikan ke 3 golongan; mereka yang beribadah karena takut dosa/neraka dan mengharap pahala/surga, mereka yang beribadah karena menari ridha Allah, dan mereka yang beribadah semata-mata karena mencintai Allah tanpa mengharap imbalan apapun.
Tak ayal pula dalam menulis. Iming-iming tersebut dapat diperdayakan untuk menjadi penyemangat. Dengan menulis, ia akan dikenal oleh orang. Ia akan bangga ketika tulisannya ter-publish secara luas. Lambat laun, tanggung jawab akademik dan sosial akan menjadi pertimbangan sendiri. Semoga.
Selain kebanggaan dan rasa percaya diri, beberapa keuntungan lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pelecut semangat menulis. Jaringan misalnya. Mereka yang sering menulis, akan mengenal dan dikenal lebih banyak orang. Pada gilirannya, ini akan menjadi kelebihan tersendiri yang dapat dimanfaatkan.
‘Keharusan’ juga dapat menjadi motivasi tersendiri. Mereka yang aktif di forum diskusi akan diharuskan untuk menulis makalah. Para jurnalis akan diharuskan untuk mengisi rubrik-rubrik. Murid akan diharuskan untuk menyelesaikan paper sebagai tugas dar gurunya. Awalnya, menulis hanya karena keharusan-keharusan ini. Namun lambat laun, seperti yang penulis alami sendiri, kegiatan menulis akan berevolusi menjadi keinginan, bukan lagi keharusan.
Kedua, strateginya? Ini bukan pertanyaan mungkin. Ini adalah tuntutan. Bukan strategi untuk mendapati laba dan keuntungan yang bejibun dari menulis. Namun lebih kepada manhaj yang paling tepat untuk menghasilkan tulisan semerdu untaian kata al-Farazdaq, namun sepadat Nihayah al-Mathlab-nya al-Juwaini. Atau setidaknya, menjadi coretan yang menyerupai ism ghair al-munsharif, tak berhak ditarik kesana kemari, merepresentasikan hanya satu makna.
Mengisi amunisi. Ini merupakan prosesi wajib, labuda, tan keno ora yang harus dilalui sebelum perang. Begitu pula dalam menulis. Sebelum memulai menulis, informasi perihal apa yang akan ditulis harus lebih dahulu dicari. Pencarian ini bisa dilakukan dengen berbagai media. Dalam komunitas akademik, membaca menjadi metode paling efektif untuk memperkaya bahan tulisan. Selain memperoleh materi, membaca dapat pula meningkatkan kekayaan diksi dan pengetahuan singkat terhadap logika serta aturan bahasa.
Oke, penulis sepakat jika membaca terkadang menjemukan. Pelbagai cara lain dapat ditempuh untuk memperkaya materi. Diskusi, sekedar mendengarkan ceramah dan seminar, atau bahkan nonton video. Variasi metode penggalian data dan informasi ini dapat menjadi alternatif untuk memperkaya wawasan.
Yang menjadi problema adalah ketika kegiatan ini dilakukan oleh mereka yang tipikalnya tidak mudah mengingat. Dalam kondisi seperti ini, notifikasi kecil selalu diperlukan. Apapun bentuk informasi yang diperoleh, dari manapun, layaknya segera didokumentasikan dalam catatan. Mungkin prinsip ini yang mengawali citra bahwa pelajar wajarnya selalu menenteng notebook dan pena. Dengan ditulis, materi itu tak mudah lenyap.
Substansi tulisan sudah lengkap, namun masalah muncul ketika tidak tahu harus mulai menulis dari mana sampai mana. Salah satu bantuan yang bisa digunakan adalah dengan membuat outline atau silabus mini. Pedoman ini nanti akan amat membantu dalam proses penulisan. Tulisan tak akan amburadul dan menjadi tak jelas.
Satu hal yang menjadi hal paling fundamental dan prinsipil dalam kegiatan apapun adalah berlatih. Tak terkecuali dalam kegiatan tulis-menulis. Semakin sering berlatih, semakin mengalir logika bahasa dan semakin menarik alur tulisannya. Mendiskusikan tulisan-tulisan itu dengan mereka yang lebih ahli juga akan menjadi poin tersendiri. Terus berlatih dan mendiskusikan tulisannya. Al-istiqamah khairun min alf karamah.
Semangat menulis sudah terbentuk, amunisi juga siap. Apalagi? Segera torehkan tinta di lembar-lembar itu! Jangan hanya sekali, namun teruslah menulis untuk mengasah ketajaman pena. Dan ingat, bersiap selalu untuk menerima undangan nge-date dari pembaca yang kagum dengan tulisan Anda! [Mc-V]

Book : “The Girl from the Coast” (translated from “Gadis Pantai”)
Author : Pramoedya Ananta Toer
Translator : Willem Samuels
Publisher : Hyperion East
Pages : 274 + 8 pages of Epilogue
Reviewer : Muhammad Miqdam Makfi
Main characters and their characteristic:
The Girl from the Coast : beautiful, smart and critical, eager to know something, egalitarian.
Bendoro : religious, wise, strict and assertive.
First Servant : simple, honest, tough and patient.
Mardinah (second servant) : pragmatic, impolite, stubborn, greedy.
Girl’s Father : harsh and strict, hard worker, deft and adroit, care, modestly.
Plot summary:
The Girl from the Coast was sent to the city. Her parents decided to give her away to Bendoro (a noble for a palace people), an aristocratic religious man in the city to be his practical wife Just like another practical wives, the Girl form the Coast was divorced right after she delivered her very first baby.
Before the marriage, she was only a daughter of a poor fisherman father and a housewife mother lived in a fishing village, somewhere near Rembang, Central Java, Indonesia. Her parents arranged the marriage for their daughter so –hopefully– she could live better than her parents. It was probably right. The Bendoro, her husband, educated her, provided all of her needs, even gave her a private servant whom she could command for anything.
Unfortunately, this rich life didn’t give her the happiness as she got in village. Her new life was cold. She felt like being a prisoner in a huge luxurious house. She could command whatever she wanted to whoever she found in the house but Bendoro, her own husband.
She therefore tried to find little happiness so she could stand staying there. Luckily, her private servant was a nice person. She helped the Girl to transform from a villager into a city woman. Also, the servant always told her the story tale before sleeping. Somehow, the Girl felt comfortable because she had a friend she could share with.
After a year being Bendoro’s wife, the Girl from the Coast started to love him. Moreover, she felt jealous when her husband went out for days. The Bendoro knew this, so he tried to be kind and lovely husband to her. But this didn’t last long. The problem occurred when Bendoro’s nephew stole the Girl’s money. Her servant then accused the nephew in front of Bendoro. As a wise-religious person, Bendoro accepted this accusation. He expelled the nephew. But also, he chased away the servant for being an impolite servant to her master with accusing his nephew.
The Girl from the Coast felt lonely. This was getting worse when Mardinah, the new servant came to replace the previous servant. In fact, Mardinah was sent by another Bendoro in Demak (another city in Central Java) to separate the Bendoro and the Girl from the Coast so Bendoro could marry the real noble woman from this another Bendoro family.
Someday, the Girl wanted to visit her family back in the village. So with Bendoro’s permission, she went to the village accompanied by Mardinah and a driver. Suddenly, the Girl didn’t want to return to Bendoro’s house. So Mardinah and the driver went back without her. After a while, Mardinah came again to the Girl’s village and told her that Bendoro asked her to go back to city. They argued until finally villagers realized that Mardinah had a tricky intention toward the Girl since the beginning she replaced the first servant. The Girl’s father punished Mardinah so she couldn’t go back to city. Meanwhile, the Girl form the Coast went back to Bendoro. After the Girl delivered the baby, Bendoro divorced her.
After this divorce, the Girl went to Blora, the hometown of her first servant.
Opinion and recommendation:
This is a novel made as a first volume of trilogy of Pram’s autobiography. Unfortunately, the second and third volumes were destroyed by Indonesian military. So, the story ends without the ending.
The Girl from the Coast is Pram’s grandmother. When she died, the young Pram promised to try to tell her story to people.
Despite the story about his grandmother, Pram, through this novel, tells the reader about the distinction found between the villager and city people, between Islamic and traditional belief people, also between proletarian and bourgeois people. Moreover, this is a story about Indonesia before it had its independence day. Using this novel, Pram tried to criticize the government which was pro-Dutch. Furthermore, Pram also implicitly tells the reader about feudalism in past time of Indonesia civilization.
To penetrate about two different classes of people and about Indonesian fighting, Pram gave the details of some places, people, and events. Sometimes, to ensure the reader about how harsh life was, these details were made very dramatically.
Because it was from Pram family’s own story, so Pram could write the novel heartfelt. In the Indonesian version, it can be seen that Pram used the proper dictions and sentences.
William Samuels translated lot of Pram’s books. So it can be sure that he really knows about Pram and his life, also about Indonesian life in past history. It can be said that William’s translation gives the reader a representative book of the original one. Only sometimes, William didn’t explain the traditional Javanese terms such pak (Indonesian word for ‘sir’), batik (Javanese cloth), etc.
Overall, those who want to read a reality based novel, critical, vulgar, historical, and memorial novel should read this Pram’s novel. Beside, The Girl from the Coast also motivates the readers to re-think and contemplate about equality and human rights.[Mc-V]

Oleh: M. Miqdam Makfi (warga PCINU Mesir)
Degradasi Masisir (Mahasiswa Indonesia-Mesir). Mungkin ini memang benar. Penulis belum bisa masuk ke ranah paradigma berpikir Masisir. Atau mungkin keluasan wawasannya, kedalaman ilmunya, dan perkara-perkara substantif lainnya. Penulis –dengan segala keterbatasan yang penulis miliki– hanya mampu menyentuh ranah fisik Masisir. Dalam istilah yang lebih lugas; bahasa Masisir.
Masisir, singkatan dari Mahasiswa Indonesia Mesir. Sebuah terma yang amat filosofis. Bagian pertama; mahasiswa. Masisir adalah mahasiswa. Resikonya, tingkah laku Masisir harus mencerminkan identitas seorang mahasiswa. Sedangkan jamak dipahami bahwa mahasiswa ideal harusnya memahami tata cara menulis dan retorika yang baik. Kemampuan bahasa baik verbal ataupun oral merupakan modal penting untuk mentransformasikan ide-idenya secara tepat, untuk bisa memberikan stigma pencitraan akan kualitas dan keseriusan mahasiswa, Dsb.
Bagian kedua; Indonesia. Sebuah negara yang pada tanggal 28 Oktober 1928 silam telah bersepakat hanya mengangkat satu bahasa; Bahasa Indonesia. Tentu pernyataan ini tidak berarti mengesampingkan bahasa daerah dan bahasa gaul yang ada di Indonesia. Jelas dipahami secara kontekstual bahwa citra bahasa Indonesia yang baik harus selalu diangkat pada tempatnya. Artinya, pada hal-hal formal, resmi, baik lokal, nasional, terlebih internasional.
Bagian ketiga; Mesir. Ini adalah fakta. Bahwa Masisir merupakan representasi bangsa Indonesia di Mesir. Mereka (baca: non-Masisir, baik penduduk pribumi Mesir, ataupun warga Indonesia sendiri yang tidak di Mesir) akan mencitrakan Indonesia –salah satunya– melalui penilaian mereka kepada Masisir. Oleh karenanya, bukan berarti menakut-nakuti, namun wajah Indonesia yang benarlah yang harus ditampilkan. Orang Mesir, misalnya, akan menilai Indonesia sebagai negara yang tidak aman ketika mereka menyadari bahwa Masisir sering tawuran atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Warga Indonesia di negara lain akan menilai miring Masisir ketika terbukti bahwa paradigma berpikir Masisir masih lemah, ketika terbukti bahwa PPMI Mesir tak mampu mengangkat nama Masisir, pun ketika terbukti bahwa Masisir tak bisa menulis maupun
berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Dari sini, penulis merasa perlu adanya penyadaran terhadap Masisir –yang belakangan dianggap regresif– tentang pentingnya bahasa Indonesia. Secara aplikatif tentunya. Artinya, Masisir tahu bahwa setiap kalimat berita haruslah diakhiri dengan titik, namun sayangnya, Masisir masih enggan membubuhkan titik itu. Sama halnya dengan seorang lelaki yang tahu bahwa wanita enggan diselingkuhi, namun ia tetap selingkuh. Muncullah stigma pencitraan itu. Tanpa membubuhkan titik (saja), Masisir bisa dianggap sebagai pihak yang menurunkan citra Indonesia. Masisir bisa dianggap sebagai mahasiswa yang tak pantas disebut mahasiswa. Okelah, dalam kasus-kasus non-formal, Masisir bebas menulis apa saja. Jangankan sekedar tak menggunakan titik, bahkan tulisannya hanya berisi titik-titik pun sah-sah saja dilakukan. Namun tentu, lain halnya jika Masisir berkecimpung dalam dunia formal. Pembuatan makalah dan karya ilmiah lain, penulisan cerpen dan novel, penyusunan Undang-Undang, redaksi media, hingga pembentukan buku merupakan tempat-tempat yang penuh rambu-rambu kepenulisan.
Belakangan, penulis mencoba mencermati beberapa tulisan yang beredar di lingkup Masisir. Ada tiga hal yang penulis soroti dari tulisan-tulisan itu. Pertama, kesalahan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) secara kasat mata. Artinya, problem-problem bahasa yang kentara dengan jelas. Problem tanda baca (titik, koma, titik-koma, Dll.), huruf kapital, awalan dan kata depan, serta transliterasi merupakan kesalahan-kesalahan umum yang hampir selalu ada di setiap tulisan. Apapun bentuk tulisannya.
Kedua, kesalahan EYD secara polemis. Maksudnya, adanya kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditentukan begitu saja melalui penyuntingan singkat, namun butuh ketelitian lebih. Permisalannya adalah kasus-kasus penggunaan konjungsi (kata sambung), pendefinisian sesuatu, dan pilihan diksi. Dalam kronologi penghitungan suara Pemilu PPMI 2009 yang disampaikan oleh jurnal PPSU, ada beberapa ayat Undang-Undang Pemilu Raya yang dicuplik. Menariknya, penulis kronologi itu mempermasalahkan kata ‘dapat’ yang tertuang dalam salah satu ayat Undang-Undang Pemilu Raya PPMI Mesir 2009. Menurutnya, kata ‘dapat’ tidak bisa merepresentasikan aturan wajib. Jika hendak diperdebatkan, kata ‘dapat’ ini sebenarnya bisa menunjukkan kewajiban. Namun tentu pihak PPSU akan tetap bersikeras dengan pandangannya itu. Lain halnya jika kata ‘dapat’ itu diganti dengan ‘wajib’ sedari awal. Pastilah penafsirannya takkan polemis. Ini merupakan sebuah kasus yang menunjukkan betapa pentingnya pemilihan diksi dalam menyusun kalimat. Jikalau penyusun Undang-Undang Pemilu kala itu memang tidak menginginkan kewajiban, maka kata ‘dapat’ memang tepat untuk digunakan. Namun jika penyusun menginginkan kewajiban, maka hendaknya tidak menggunakan kata ‘dapat’ yang walaupun bisa menunjukkan kewajiban, namun bisa juga diolor-olor ke sana ke sini oleh berbagai pihak.
Ketiga, ideologi dan subyektivitas. Ini bukan merupakan kesalahan penulisan. Namun ini merupakan hal yang patut diperhatikan pembaca tulisan Masisir. Tak sedikit tulisan Masisir yang diwarnai oleh semangat ideologis. Walhasil, diksi yang dipilih, logika yang digunakan, dan model penyampaian yang dipakai merupakan bias ideologi penulis. Oleh karenanya, kehati-hatian dan ketelitian membaca perlu adanya agar pembaca bisa lebih obyektif. Tidak terbawa ideologi penulis.
Yang membahayakan adalah imbas dari dua model kesalahan EYD yang telah penulis kemukakan. Efek negatif pertama adalah menurunnya ketelitian Masisir. Jika Masisir tetap tidak mengindahkan pedoman EYD, maka Masisir akan terbiasa untuk tidak mengindahkan hal-hal partikular yang dianggap kecil dalam kehidupan. Imbas yang kedua, adanya kesalahan EYD menunjukkan keengganan penulis untuk mengedit dan membaca ulang tulisannya. Ini penting. Karena, dengan menyunting dan membaca ulang tulisan, selain membenarkan EYD yang ada, penulis juga dapat membenarkan analisis yang kurang tepat ataupun data yang tidak valid. Sedangkan problem terakhir yang sering kali muncul dari kesalahan EYD ini adalah ambiguitas tulisan. Sering kali, penafsiran yang dimunculkan oleh pembaca, lepas, bahkan melenceng jauh dari apa yang diharapkan oleh penulis.
Maka penulis hanya bisa berharap akan adanya kesadaran komunal Masisir dalam memperbaiki tulisannya sebagai langkah awal dalam memperbaiki Masisir ke depan. Semoga.[]
Sejak 1955, kala Pemilu pertama diadakan di Indonesia, demokrasi Pancasila resmi menjadi ideologi politik Tanah Air. Rakyat Indonesia kala itu tentram dan puas karena para pemimpin negaranya dipilih dan diangkat oleh rakyat sendiri. Kedaulatan rakyat, seperti termaktub di batang tubuh UUD 1945 pasal 1, benar-benar mengencani perjalanan politik di Tanah Pertiwi.
Keintiman rumah tangga ini mulai dirusak ketika orde baru naik menjadi pengatur negara, dipimpin oleh Bpk. Suharto. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa peran beliau dalam membantu kemerdekaan amatlah mulia. Bahkan, niatannya ketika menjabat jadi Presiden pun tidak dapat dikatakan negatif. Namun manusia tetaplah manusia. Hingga Pak Harto pun tak luput dari problematika individual-psikologis ketika menjadi Presiden RI.
Jika diamati, problematika politik Indonesia –dalam ketidaksadaran bangsa– mulai lahir di masa-masa Orba. Bisa jadi, sofistifikasi politik –salah satu problem inti yang kemudian dikesankan menjadi simplifikasi politik oleh rezim Orba dengan hanya membentuk 3 Parpol pada bentang 1977-1997– adalah kelatahan Indonesia terhadap gelombang ketiga demokrasi dunia kala itu. Samuel P. Huntington telah mengkisahkan bahwa gelombang ketiga demokrasi ini muncul sejak revolusi Portugal di tahun 1974. Terhitung 60 negara dari Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan (tentunya) Asia latah dan mengikuti arus gelombang ini. Para pengamat politik berasumsi bahwa ini bukan hanya kelatahan dalam dunia demokrasi an sich. Namun kelatahan ini meruyak hingga unsur ‘terpimpin’ dalam sistem demokrasi itu. Maka di dekade 80-an, menjamurlah negara-negara demokrasi terpimpin seperti Mesir dengan Husni Mubarak-nya, Paraguay dengan Alfredo Stroessner-nya, Philipina dengan Ferdinand Marcos-nya, Sudan dengan Umar Hasan al-Bashirnya, Indonesia dengan Pak Suharto-nya, diikuti negara-negara lainnya.
Indonesia pantas bersyukur karena dengan suatu hal dan lainnya, demokrasi terpimpin Suharto dapat digugurkan menjelang milenium ketiga. Walhasil, demokrasi Pancasila kembali dihadirkan menggantikan demokrasi terpimpin milik Orba. Kini, rakyat yang memiliki wewenang untuk menentukan jalan hidup Indonesia.
Pemilu 2009 semakin dekat. Maka rakyat Indonesia pun kembali diajak bermusyawarah menentukan nasib bangsa. Bukan hanya mereka yang ada di Tanah Air, namun kita yang hidup di luar negeri pun dihargai dan diberi hak untuk ikut menentukan arah jalan bangsa Pertiwi. 38 Parpol yang terdaftar diharapkan mampu membawa Indonesia menuju tatanan yang lebih baik. Dengan jumlah yang tidak sedikit ini, rakyat memang dituntut untuk lebih jeli mengkualifikasi Caleg dan Parpol yang ada. Bukan dengan ketenaran belaka. Apalagi dengan sodoran amplop yang ditawarkan. Rakyat Indonesia telah berumur 63 tahun lebih. Bukan lagi anak kecil yang dengan mudah bisa dibohongin. Namun seorang dewasa yang mampu berpikir jernih untuk menentukan keputusan.
Akhirnya, penulis hanya ingin menegaskan bahwa satu hak pilih yang kita punya adalah satu titik dari garis start Indonesia untuk melangkah ke depan. Dan iya, sebuah garis tak kan pernah lengkap tanpa kelengkapan titik-titik yang menyusunnya. Jika kita memang yakin bahwa tidak ada satu pun Caleg dan Parpol terbaik untuk dipilih, maka kita tetap harus gengsi jika Indonesia dipimpin oleh Caleg dan Parpol yang terburuk. Ke mana Indonesia melangkah? Siapa yang akan membimbing bangsa kita? Temukan jawabnya pada diri kita masing-masing! Diri kita sebagai bangsa Indonesia tentunya, bukan yang lain.[]
Sebuah fakta jikalau kita berujar bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tertinggal dalam skala internasional. Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan oleh Organisation for Economi co-Operation and Development (OECD) tiap tiga tahun sekali membuktikan hal itu. Tes terakhir pada tahun 2006 menaruh Indonesia di papan bawah klasemen. Indonesia berada di peringkat 48 dari 56 negara dalam kategori ‘aktivitas membaca’. Sedangkan dalam dua kategori lainnya –science dan matematika– Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 50 dari 57 negara. Jangankan di atas negara-negara maju, bahkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Estonia, Latvia, Lituania dan lainnya pun Indonesia masih tertinggal. Negara-negara yang berada di bawah Indonesia adalah negara-negara kecil berkembang seperti Kirgistan, Qatar ataupun Montonegro.
United Nation of Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang bergerak di bawah Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkapkan sebuah konklusi yang sama. Berikut data terakhir di tahun 2006:
Prosentase Pendaftar Jenjang Pendidikan Dasar:
Jepang : 100%
Inggris : 98%
Indonesia : 96%
Amerika Serikat : 92%
Prosentase Pendaftar Jenjang Pendidikan Menengah:
Jepang : 99%
Inggris : 92%
Amerika Serikat : 88%
Indonesia : 59%
Sebenarnya, ditilik secara kasat mata tanpa data statistik pun dapat dirasakan. Konon, tenaga pendidik di negara tetangga seperti Malaysia, banyak yang berasal dari Tanah Air. Bahkan, pada abad 16 hingga 18 Masehi, regional Asia Tenggara Kecil yang dikenal ‘Nusantara’ didominasi oleh tokoh-tokoh Indonesia. Namun sekarang, para pelajar Pertiwi justru bangga ketika mampu meneruskan jenjang studinya ke Selangor atau ke UM (Universiti Malaysia) di Kuala Lumpur
Berangkat dari fenomena riil ini, banyak kalangan yang saling berebut. Berebut untuk menentukan apa, siapa dan mana yang salah. Sebagian lain lebih berpikir rasional dengan berusaha mencari pangkal benang kusut ini. Di sini penulis setuju dengan klasifikasi terhadap faktor kegagalan pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Frenky Suseno Manik, S.Si. alumnus FMIPA UGM. Sarjana sains ini mengklasifikasikan faktor kegagalan pendidikan Indonesia ke dalam dua hal: Masalah mendasar (faktor umum) dan masalah cabang (khusus). Permasalahan mendasar mencakup sitem pendidikan yang di-setting oleh pemerintah, sedangkan masalah cabang menyangkut hal-hal parsial yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia –yang begitu rendahnya.
Penulis sepakat sampai di sini. Jika kemudian Franky mensinyalir sistem pendidikan yang sekular-materialistik sebagai poros yang hancur dan menghancurkan pendidikan Indonesia, maka penulis lebih meyakini kurikulum memori-sentris sebagai penghalang fundamental terhadap perkembangan pendidikan Indonesia. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk Kementrian Pengajaran yang berfungsi sebagaimana Depdiknas kini. Semenjak itu, dimulailah pendidikan formal yang tersistem di Indonesia. Dan semenjak itu pulalah rakyat Indonesia dituntut untuk mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bersifat memori-sentris.
Di lain sisi, edukasi formal di Indonesia menggunakan sistem top down education. Sedari kecil, siswa-siswi dituntut untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh tenaga pengajar (baca: guru). Bersyukur karena belakangan (pasca reformasi), guru memberi ruang lebih banyak untuk berdiskusi. Hasilnya pun terlihat, survey OECD menyatakan bahwa dalam dekade terakhir ini kemampuan science, matematika dan membaca warga Indonesia berkembang cukup drastis.
Pola pembelajaran yang mengoptimalkan diskusi ini merupakan upaya untuk menciptakan sistem bottom up di Indonesia. Namun, ini jauh dari sempurna jika para pelajar masih acap kali dituntut untuk menghapal, bukan menganalisis. Memahami seluruh materi akan menjadi sia-sia jika ketika ujian datang, masih harus ngerpek. Siswa diharuskan mengandalkan kekuatan otak kirinya dalam menghapalkan seluruh materi yang telah disampaikan.
Kerusakan pola pendidikan ini disepakati oleh J. Riberu. Beliau adalah mantan rektor sekaligus dosen di UNIKA Atma Jaya. Beliau juga sempat menjadi dosen di UI dan IKIP. Aktivitas lain beliau pun cenderung menjurus pada pendidikan seperti Dokpen MAWI dan LPPM. Tokoh pendidikan ini mendapatkan gelar Doktor Pedagoginya di Universitas Salesiana, Roma, Italia. Dalam buku “sang Pedagog dari Ngada: Identitas Sosok Jan Riberu”, Yosef Dedy Pradipto (penulis buku) menyematkan gelar Maestro Pedagogi kepadanya.
Dalam sebuah makalahnya, Jan Riberu menyayangkan pola pendidikan Indonesia yang logis deskriptif dan berpusat pada kekuatan ingatan. Harusnya, para pelajar dituntut untuk mandiri, sehingga menjadi jebolan yang kritis, kreatif dan inovatif. ‘Sekolah Dengar’ sudah tidak layak lagi dijadikan standar kelembagaan pendidikan Indonesia. ‘Sekolah Aktif’-lah yang harusnya menjadi pijakan Depdiknas dalam mengatur pendidikan di Indonesia. Siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan panduan dan modal dasar yang diberikan guru, bukan malah dijejali dengan berbagai materi untuk kemudian dijadikan pertanyaan dalam ujian nanti. Tidak akan ada perbedaan kualitas SDM sebelum ujian dan setelahnya. Bedanya hanyalah opened book dan closed book.
Hipotesis ini diakui pula oleh beberapa tokoh internasional seperti Paulo Freire, Ivan Illich dan David Ulrich. Bahkan, ilmuwan zoologi ternama, Peter B. Medawar, mengiyakan pula hipotesa ini, walaupun dengan bahasanya sendiri. Profesor di University of Birmingham dan University College London yang memperoleh Nobel di berbagai temuannya ini menegaskan bahwa semakin kreaitf seseorang menciptakan alat belajarnya sendiri, semakin besar pula kemungkinan suksesnya. Di kesempatan lain beliau pernah berujar, “Terkadang, nalar dan pikiran manusia harus benar-benar dilepaskan dan dibebaskan dari segala macam belenggu. Bahkan dari jati dirinya sendiri. Semakin liar pikiran itu, maka semakin banyak pula inovasi-inovasi yang ditemukan. Kebenaran penemuan harus dijadikan nomer dua. Bebasnya nalar dan kreativitas manusia itu yang menjadi prioritas.”
Sedangkan dalam kategori faktor khusus, penulis menemukan pelbagai materi yang mempengaruhi kemerosotan pendidikan di Indonesia. Pertama, minimnya kesadaran pendidikan yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun, para peminat IKIP dan LPTK semakin menurun. Alumnus-alumnus berbakat lebih senang mencari jurusan yang prospektif seperti tekhnik dan kedokteran, daripada jurusan pendidikan. Di lain sisi, standar penerimaannya pun tidak terlalu tinggi. Ini mengakibatkan, para calon tenaga pengajar lebih banyak berasal dari kalangan intelek menengah ke bawah.
Kedua, dekadensi moral bangsa Indonesia. KKN yang merajalela di kalangan politisi, para pelajar yang doyan tawuran, dugem, aksi pornografi dan pernak-pernik lainnya cukup dijadikan refleksi kebiadaban moral bangsa Indonesia. Bahkan pencantuman nilai minimal kelulusan dalam UAN disinyalir oleh sebagain kalangan sebagai dampak imoralnya Indonesia. Pengejawantahan pola yang belum siap diterima hanya akan menimbulkan problematika lain. Bukan hanya siswa, namun tenaga pengajarpun akan cenderung mencari jalan pintas agak anak didiknya mampu melewati UAN dengan sukses. Akibatnya, tujuan prinsipil dari proses pendidikan tidak lagi diindahkan. Permasalahan moral ini harusnya menjadi tanggung jawab pendidikan keluarga dan agama. Oleh karenanya, penerapan RUU Pornografi –misalnya– bukan jalan keluar solutif terhadap meruyaknya dunia pornografi di Indonesia. Optimalisasi pendidikan informal adalah solusi sedari awal yang harusnya mampu menyelesaikan problematika moralitas bangsa Indonesai ini.
Ketiga, kepasrahan masyarakat. Pemberlakuan sistem pengajaran yang tidak tepat di pendidikan diabaikan oleh masyarakat. Ketika ada kebijakan baru, masyarakat (baik siswa maupun pembimbing) kurang kritis dalam memahami kebijakan itu. Akibatnya, ketika muncul kebijakan yang menyimpang dari tujuan pendidikan, tidak ada yang merasa keberatan. Sebagai sebuah permisalan, materi yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah formal selama ini amat menjurus pada hal-hal yang tidak diperlukan. Dunia pendidikan lebih menjadi penyalur kebudayaan daripada produsen kebudayaan. Akhirnya, modernisasipun terhambat karena pelajar masih diajarkan cara menguasai cowek/ulekan ketika negara lain telah lihai menggunakan mixer/blender. Harusnya, pembelajaran materi-materi yang mendukung masa depan siswa lebih diperhatikan. Penguasaan komputer dan bahasa Inggris misalnya –yang menjadi modal utama berkarir di dunia kontemporer– dijadikan nomer sekian dalam dunia pendidikan. Bahkan kadang hanya menjadi tanggung jawab kursus dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun siswa dan orang tua tidak pernah protes dan mempertanyakan hal ini.
Keempat, finansial. Masyarakat sering menuduh mahalnya pendidikan sebagai biang kebodohan bangsa. Salah satu faktornya adalah belum meratanya Kebijakan pemerintah dalam penggunaan APBN dan otonomi daerah untuk memberi tambahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru dan dana pendidikan lain. Tujuan gratis pendidikan dasar yang diangkat pemerintah terlalu general. Harusnya, gratisnya biaya sekolah dasar hanya diberikan kepada kalangan tidak mampu, sehingga anggaran yang tadinya akan digunakan untuk membiayai orang kaya, dapat dialokasikan ke aspek lain. Guru misalnya. Kesejahteraan dan prestise guru harus dinaikkan sehingga ke depan, image seorang guru menjadi tinggi dan mulia. Dan diharapkan, intelek yang bermutu, berlomba-lomba untuk memperoleh posisi ini.
Akhirnya, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa runyamnya dunia pendidikan ini tidak perlu dianggap kompleks. Kita tidak seharusnya menjadi pembaca setia yang hanya bangga ketika bisa mengangguk-angguk setuju dengan yang ada. Atau justru sebaliknya. Kita harusnya menjadi bangga ketika kita mampu bergerak merespon wacana itu. Kalau mustahil dilaksanakan secara deduktif, pastilah ada usaha induktif. Berangkat dari hal yang paling parsial. Diri kita sendiri. Terima kasih [Mc-V]
Pancasila. Kehadirannya memang bermakna amat mendalam. Tak usah memutar memori menuju tahun kelahirannya. Beberapa waktu lalu, tepat di ulang tahunnya, 1 Juni 2008, eksistensinya sudah terkesan begitu dahsyat. Rakyat Bumi Pertiwi geger oleh sebuah peristiwa ganas. Katakanlah Ahmadiyah. Selaku penyebabnya tentu. Sebuah kelompok –yang mengaku Islam– yang muncul dengan ideologi barunya –berupa ketidakpercayaannya pada kenabian Muhammad Saw– di tengah-tengah keterpurukan Islam kini. Salah tentunya, jika dipadankan dengan Ahmadiyah Pakistan. Buktinya, produk Nusantara yang ini masuk kategori ‘aliran’ Islam dalam kacamata khalayak maupun kalangan elit (baca: Pemerintah dan ulama/pemikir).
Tak perlu diungkit memang. Biarlah kelahiran Ahmadiyah menjadi sebuah kenangan saja. Poros kali ini adalah FPI dan AKBB. Sang pemilik hak sengketa.Keduanya diklaim sebagai ‘yang salah’. Oleh berbagai lapisan pihak tentunya. Pertanyaan favoritnya adalah: Siapa yang sebenarnya salah?
Sekali lagi. Pancasila benar-benar menunjukkan kedahsyatannya. Ketuhanan. Insiden itu teracik serta diniati untuk dirampungkan oleh dan demi apologi-apologi religius. Kemanusiaan. Konfrontasi fisik mana yang tak mungkin dikecam oleh prinsip ini? Persatuan. Tidak munafik kalau insiden tersebut bakalan menentukan masa depan salah satu rumusan Pancasila ini. Kerakyatan. Kasat mata tentunya keberadaan rakyat sebagai pelaku kasus ini. Keadilan. Haruslah dipikirkan bersama keberadaan pihak-pihak yang diadili dan merasa mengadili. Apakah semuanya benar-benar adil?
Ah, benar rupanya. Pancasila ada di sekitar kita. Bahkan rasanya ia ingin merayakan ulang tahunnya di tahun kabisat kali ini. Mungkin sudah benar ketika ia mengadakan pesta perayaan. Sayang saja para undangan tidak menghadirkan kue ulang tahun yang indah. Namun justru bom molotov yang merekah.
Zeyno Baran, S. Frederick Starr, dan Svante E. Cornell sepakat bahwasanya tahun 1980 merupakan awal mula berkembang pesatnya radikalisme Islam. Kala itu Uni Soviet yang berhasil menjadi tanah suburnya. Sebuah kesepakatan sosial pastinya, jika radikalisme ini merebak dan meluas ke teritorial lain.
Sampailah di Indonesia. Kekerasan dalam Islam itu lambat laun mulai terpatri pula dalam sanubari Muslimin Indonesia. FPI menjadi salah satu poros yang memang terkenal aduhai dalam pengkaderan masa berjiwa fundamentalis ini. Benar memang jika fundamentalis bukanlah radikalis. Mereka mengawali kiprahnya dengan sebuah niatan tulus; mengembalikan Islam kepada hakikatnya. Sayangnya, sesuai genealogi yang ada, niatan yang tulis ini tidak diembankan kepada tenaga aplikatif yang memadai, sehingga melahirkan varian interpretasi religius yang ngawur dan amburadul. Mencuat sudah terma radikalisme untuk golongan ini.
AKBB, sebuah aliansi di sudut lain yang berusaha menetralisir hal ini. Mereka bergerak dengan cara pragmatis yang lebih halus. Hanya saja, pertautan ideologis akan benar-benar menjadi tembok besar antara mereka dan kaum fundamentalis (baca; radikalis) yang mulai merasa menemukan Islamnya. Akhirnya, dari peperangan ideologi inilah tersulam benang-benang ketegangan satu sama lain. Puncaknya ketika Ahmadiyah muncul sebagai sebuah aliran sesat yang membawa nama Islam. Bak terpukul palu keras dari belakang, kalangan fundamentalis berusaha membalas pukulan itu dengan tindakan yang lebih keras. Sebaliknya, golongan yang lebih bijaksana berusaha menyelesaikannya dengan cara yang lebih halus.
Ahmadiyah memang salah, bahkan nomenklatur ‘bajingan’ lebih tepat disematkan padanya. Ia telah menjadi sebuah bola yang diperebutkan kedua tim. Satu tim ingin melepaskan tendangan kerasnya kepada bola itu menuju gawang. Sedangkan tim lawan lebih bermain tekhnik dan berharap mampu melesatkannya ke dalam gawang dengan gaya akrobatik. Naas rupanya, entah karena apa, sang wasit tidak mampu mengamati pertandingan dengan seksama. Aturan-aturan main yang telah ditetapkan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) dilanggar begitu saja tanpa respon jelas dari wasit. Bahkan untuk menentukan pelanggaran atau tidak, wasit masih harus menyaksikan tayangan ulangnya. Lalu bagaimana dengan offside yang tentunya lebih membutuhkan kejelian, kecepatan, dan keputusan untuk mengambil keputusan?
Layaknya PSSI dan wasit dalam persepakbolaan Indonesia, pemerintah dan (mungkin) MUI, harus benar-benar mampu mengawasi jalannya pertandingan dengan baik. Ketika terjadi pelanggaran, siapapun itu harus segera ditindak. Pun ketika keduanya bersalah, tak segan pula wasit harus mengeluarkan kartu peringatan untuk keduanya.
Di lain sisi, bola bundar yang menjadi titik fokus utama dalam sebuah pertandingan harus diperhatikan. Sebuah bola yang berduri dan beracun tentunya harus disingkirkan dari lapangan hijau. Akan tetapi, meledakkan bola ini di tengah pertandingan pastilah menimbulkan kegemparan pemain dan penonton. Pemerintah harus benar-benar memiliki konsep yang cantik untuk mengantisipasi gerakan Ahmadiyah menghancurkan Islam, tanpa mengacuhkan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam berkebangsaan.
Martin Van Bruinessen pernah bertutur, lembar historis menyatakan bahwa Islam di Indonesia –bahkan di dunia– amat berkelindan dengan politik. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pernah –tanpa sadar– memiliki dualisme ideologis. Di satu sisi mendukung –dan didukung tentunya– gerakan Sukarno-Hatta untuk mengapresiasi demokrasi Barat dan ajaran neo-patrimonialnya. Namun di sisi lain, dengan keyakinan fundamentalnya mereka berusaha menepis dan menganggap ajaran yang datang dari luar Islam sebagai sebuah penyakit serta marabahaya. Lebih terlihat politisnya, ketika lembaga ini ‘ketahuan’ menjalin hubungan dengan Rabithah al-‘Alam al-Islami yang berpusat di Saudi Arabia.
Kini juga pasti seperti itu. PSSI harus mengindahkan kemungkinan permainan politik para pemain Indonesia, apalagi ketika politik itu sampai terjalin keluar. FIFA selaku pemilik kekuasaan mutlak di dunia pastilah merasa jengkel. Oleh karenanya, permasalahan Ahmadiyah –dan segala seluk beluknya– ini harus segera diselesaikan dengan finishing yang indah. Kalau memang harus menentukan pemenangnya, lempar koin-pun dapat ditetapkan. Tentunya jika solusi terakhir itu memang menjadi langkah yang paling tepat.[]
Belakangan ini terasa ada semacam pemiskinan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bukan hanya kebutuhan sekunder dan tersier, namun hingga barang-barang pokok pun mengalami kenaikan harga yang amat menyesakkan. Fenomena ini tentunya menimbulkan efek yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Seperti biasa, seperti halnya ketika ada masalah ini itu dalam berbagai keputusan pemerintah, demo-demo mulai marak terjadi. Berbagai golongan berusaha untuk meyakinkan pemerintah bahwasanya keputusan mereka ini salah. Kenaikan BBM dan harga-harga pokok lain merupakan langkah tidak solutif terhadap problematika bangsa. Pemerintah dipaksa untuk melihat dan ikut merasakan penderitaan kalangan ekonomi lemah dalam menerima keputusan yang inhumanis ini.
Saya, selaku bangsa Indonesia, sedih mendengar kekacauan kecil yang menimpa Tanah Air ini. Entah karena saya sendiri tidak merasakan kekurangan, atau karena hal lain, namun saya merasa ketidakterimaan masyarakat ini terlalu berlebihan.
Kesalahan harusnya dilemparkan kepada rezim orde baru, yang pemimpinnya belakangan waktu lalu telah meninggal (baca: Bpk tercinta Ir. Soeharto). Apresiasi tinggi layak dinisbatkan kepada mantan Bapak Negara tersebut. Dengan jerih payah dan pengorbanan yang tak sedikit, beliau telah berupaya untuk menjaga stabilitas negara, ekonomi khususnya. Rakyat kecil pasti tau itu. Mereka pasti merasakan kehidupan yang berkecukupan, dan tentunya, tidak sesulit sekarang ini. Harga-harga kebutuhan dapat dikatakan stabil. Mungkin 'murah' adalah terma yang lebih tepat.
Masa silam itu harusnya tidak terkubur begitu saja. Selidik demi selidik, beberapa kalangan sempat meyakini bahwa stabilitas harga kala itu hanyalah kebohongan belaka. Secaya hiperbolis, pemerintah Orde Baru berusaha untuk membahagiakan rakyat dengan memberikan subsidi yang sebesar-besarnya. Mungkin benar jika ada yang bilang bahwa itu hanyalah langkah politis belaka, agar kekuasaannya tetap dipercaya. Namun fakta berbicara, bahwa subsidi-subsidi tersebut amatlah menguras harta negara, yang secara tidak langsung merupakan harta rakyat, walaupun tak pernah dihayati secara utuh.
Sebuah penggambaran yang harusnya dihayati; misalkan saja harga bensin premium per-liternya adalah 7.000 rupiah. Pada rezim Bapak Soeharto, pemeritah memberikan subsidi gila-gilaan –yang entah dapat utangan dari mana– hingga akhirnya seluruh rakyat dapat memperoleh bensin premium hanya dengan harga 2.000 pe-rliter. Ini berarti pemerintah memberikan subsidi 5.000 rupiah untuk tiap liter bensin premium. Jika per-harinya sebutlah 10 juta liter bensin dikonsumsi, berarti pemerintah memberikan subsidi sebesar 50 milyar. Tiap bulan akan membutuhkan 1,5 trilyun rupiah. Sudah ada berapa anak tak mampu yang bisa sekolah dengan uang itu??
Setelah Soeharto mangkat, pemerinta berusaha realisitis, subsidi yang gila-gilaan tersebut dikurangi hingga akhirnya rakyat harus merogoh koceknya sampai 5.000 rupiah demi membeli satu liter bensin. Rakyat akan merasa amat shock. Namun sayangnya, rakyat tidak menyadari, bahwa harga 5.000 itupun sebenarnya sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Proses pengurangan subsidi di satu aspek demi meningkatkan subsidi di aspek lain dan juga kebutuhan negara lain, harusnya diterima secara wajar. Bukan justru dihujat untuk kembali menaikkan subsidi tersebut. Lebih lagi, akhirnya uang yang dihemat pemerintah itu nantinya pasti kembali ke rakyat, hanya saja bukan berupa bensin lagi. Beasiswa studi meningkat, banyak sekolah-sekolah gratis untuk siswa tak mampu, dan realisasi lainnya yang diwujudkan pemerintah.
Berangkat dari penggambaran seperti, harusnya rakyat tidak merespon keputusan pemerintah secara frontal. Langhkah pemerintah ini merupakan sebuah tindakan yang mengutamakan fairness. Harga murah yang awalnya bisa didapat oleh setiap golongan rakyat, dirubah oleh pemerintah menjadi harga mahal untuk semua golongan, dengan bagi-bagi gratis untuk para ekonomi lemah. Ini artinya, pemerintah benar-benar realistis. Orang kaya harus bayar mahal untuk satu liter bensin, namun orang miskin justru mendapatkan barang-barang gratis. Artinya, harusnya orang miskin tidak merasa dirugikan.
Fakta berkata, 19 juta lebih rumah tangga memperolah bantuan tunai dari pemerintah. Kalangan ekonomi lemah lain juga diberi beras 15kg per bulannya. Silahkan baca faktanya di SINI
Akhir kata, saya hanya ingin mengingatkan kepada para demonstran itu....cermati lebih dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pada tulisan ini, saya sama sekali tidak menyebut hal-hal ke-luar negeri-an yang sebenarnya amat mempengaruhi keputusan pemerintah tersebut. Saya yakin, para demonstran itu akan amat terpukul dan malu tentunya ketika tahu dan sadar, betapa kompleksnya pertimbangan yang diambil oleh pemerintah. Namun tentunya, demo-demo itu tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Mengapa? Tentunya karena sudut pandang rakyat jugalah yang menjadi salah satu determinan mengapa pemerintah mengambil keputusan itu....thanks
Berbicara tentang Islam Nusantara pastinya akan menyentuh ranah sejarah karena memang Islam hadir dan meluap di tanah air melalui pijakan-pijakan historis. Dalam L’arabie et les Indes Neerlandaises, Snouck Hurgronje menjelaskan bahwa pada abad 12-13 Masehi (awal Islam di Indonesia), tidak ditemukan unsur-unsur Arabisme dalam tubuh Islam Indonesia. Pada masa-masa ini pula hubungan Indonesia dan India terkesan romantis. Oleh karenanya Snouck berkeyakinan –dan diimani oleh para sejarawan Barat hingga kini– bahwa Islam hadir di Indonesia berkat kiprah bangsa India sebagai mediatornya.
Di sisi lain, beberapa kalangan yang menelusuri jejak Islam Nusantara mengocehkan bahwa Islam Indonesia merupakan Islam Persia yang masuk sekitar abad 13 Masehi melalui kekuasaan kerajaan Samudra Passai. Ini disandarkan pada realitas sejarah kala itu yang mengisahkan keidentikan ritual agama di Indonesia dengan Persia.
Ternyata benang ruwet ini tidak berhenti begitu saja, pendapat yang justru lebih dikuatkan adalah yang mengatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke 7 (awal abad hijriyah). Kedatangan Islam ini tak lepas dari pengaruh hubungan liberal China dengan Arab. Dalam kitab sejarah China yang bertajuk Chiu T’hang Shu diumbar bahwa pada tahun 651 M/31 H, China kedatangan duta utusan dari Arab. Padahal, seperti diketahui bahwasanya pada masa-masa ini, Nusantara cukup terkenal dimata dunia, khususnya dalam bidang perdagangan. Untuk itu, kemungkinan sangat besar para duta Arab yang dikirim ke China terlebih dahulu mampir di Indonesia sebelum kembali ke Arab. Hal ini dikuatkan dengan catatan sejarah yang penulis temukan dari tulisan Azyumardi Azra, bahwa pada tahun 671 Masehi, kunjungan I-Tsing dari China ke pelabuhan Sribuza (Sriwijaya) mencatat kehadiran orang-orang Arab dan Persia di Indonesia.
Dari sini, hubungan diplomasi Indo-Arab (Islam) yang dijembatani oleh China menjadi semakin tersemai. Bahkan, pada tahun 718 M/100H, Sri Indavarman (raja Sriwijaya kala itu) sempat mengirimkan surat kepada khalifah terkemuka, Umar bin Abdul Aziz untuk meminta utusan dari Arab yang dapat mengajarkan Islam di Indonesia. Akhirnya, perawaban Islam di Indonesiapun mulai terbentuk dan menggantikan hegemoni Hindu-Budha yang sudah ada sejak dulu.
Terlepas dari asal usul kelahiran Islam di Nusantara, terlintas kata sepakat ketika ada kesimpulan bahwa Islam hadir bukan dengan dakwah formalis, namun justru dengan perangkat lain seperti perdagangan. Pun penyebaran Islam di Indonesia dan sekitarnya, lebih terkesan kultural, tidak puritan, sehingga mampu mendekati warga dengan ajakan persuasif.
Berangkat dari kenyataan ini, wajarlah sudah jika Islam dahulu memang lebih melekat kuat dalam sanubari para penganutnya. Entah memang tidak ada, atau karena belum ada, tidak kita temui terma “Islam KTP” dalam rakitan sejarah pra modernitas. Warga Islam Nusantara saat itu memang benar-benar Islam, dengan sepenuh hati meyakini dan mengamalkan ajaran agama ini. Wali Songo yang merupakan pionir dakwah Islam Nusantara menjalankan misinya dengan amat sempurna. Loyalitasnya yang merakyat, kemampuan diplomasi yang disegani pemerintah, serta metodologi dakwah yang membudaya membuat warga tercerahkan dan dapat memhamai Islam yang benar-benar mendamaikan dan mensejahterakan umat.
Pada babak-babak sejarah selanjutnya, nama-nama seperti Syaikh Nawawi al-Bantani, Nuruddin al-Raniri, Syaikh Ihsan Ibn Dahlan al-Jamfasi al-Kadiri, serta tokoh lain mulai meramaikan perjalanan Islam Nusantara. Produktifitas mereka dalam menciptakan pelbagai buah karya Islami patut diapresiasi setinggi-tingginya. Bahasan buku-buku yang mereka anggit seolah amat menyentuh kehidupan sosial masyarakat sehingga mudah untuk diterima. Dengan semangat menuntut ilmu yang tinggi, bahkan hingga mencoba untuk memperkaya ilmunya melalui pembelajaran di luar negeri, Timur Tengah khususnya, menjadikan mereka tokoh-tokoh berwawasan luas yang disegani oleh rakyat Nusantara.
Keseragaman yang mereka angkut menjadikan mereka mampu menyebarkan Islam di Indonesia dengan kebersamaan yang saling melengkapi. Mulai didirikannya pondok pesantren salafi kala itu merupakan wujud dari kekompakan semangat mereka dalam mendakwahkan Islam. Martin Van Bruinessen merupakan salah satu peneliti Kitab Kuning dan Pesantren Melayu yang amat mengapresiasi usaha mereka ini. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia memberikan andil yang amat luar biasa dalam menyebarkan ajaran Ilahi. Benar jika dikatakan bahwa buku-buku dan kajian di pondok pesantren terkesan tertutup dan tidak menerima pemikiran yang agak nyeleneh. Pun tradisi santri dan murid untuk mengagungkan gurunya dan tanduk patuh terhadap apa yang diajarkan serta yang diperintahkan memang amat menggema di masa itu. Namun, metodologi dan corak pembelajaran seperti itulah yang memang sedang dibutuhkan. Ketidaktahuan masyarakat akan hakikat agama perlu diselaraskan. Pengenalan dasar akan Islam yang merupakan agama baru di Indonesia kala itu perlu diseragamkan sehingga nantinya tidak muncul konfrontasi antara orang baru dalam Islam.
Lambat laun, modernitas mulai merajalela hingga masuk ke dalam konstruk sosial Indonesia. Mirisnya, kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini tidak diimbangi dengan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Yang dilestarikan oleh Muslim Indonesia modern, bukanlah semangat keilmuan pada ulama klasik yang permanen sehingga bisa diaplikasikan kapan saja, tapi justru metodologi salaf yang temporal dan dibatasi oleh berbagai hal. Kemirisan ini menjadikan Islam di Indonesia justru lebih mandeg daripada kemandegan yang dialami Timur Tengah belakangan ini. Jangankan dibandingkan dengan Amerika dan kawan-kawan, dibandingkan dengan Malaysia saja mungkin Islam Indonesia masih terlampau kalah jauh.
Realitas adalah kenyataan yang harus diterima, namun kenyataan ini bukanlah keyakinan yang harus terendapkan. jikalau memang Roma masih ada, maka masih banyak pula jalan menujunya. Ini bukan nol, bukan pula pemberhentian terakhir, namun ini adalah kenyataan pahit yang harus dijayakan kembali. Dahulu, al-Bantani dkk. mampu menunjukkan pada dunia akan eksistensi Islam di Indonesia dengan usaha keras mereka hingga rela mempelajari Islam dari kiblat Islam kala itu (Arab). Tentunya, tidak mustahil bagi generasi sekarang untuk turut semangan meniti karir mereka dengan mempelajari Islam dari berbagai tempat yang memang pantas dan layak untuk dijadikan referensi kajian Islam. Islam memang lahir di Jazirah Arab, akan tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa belakangan ini, kajian Islam di Barat lebih berbobot dan lebih otoritatif. Bukan berarti hendak menyerahkan Islam kepada mereka, namun justru dengan menyerap ilmu yang ada di sana (layaknya mereka mengembat ilmu-ilmu dari Islam Arab sejak abad 11 dulu) kita mampu kembali merebut Islam ke tangan kita.
benar, pada zaman al-Bantani dkk. paradigma kajian Islam Timur Tengah masih terkesan jumûd. Dengan melihat realitas sejarah bahwa karya-karya yang muncul kala itu hanyalah karya-karya berbentuk syarh, hasyiyah, dan semacamnya, dapat dimengerti bahwa kajian dan ide-ide keagamaan kala itu benar-benar stagnan. Namun semangat, yang diusung oleh ulama Islam Nusantara pada zaman itu perlu dilanjutkan oleh anak-anak bangsa. Produktifitas yang telah seabad lebih musnah harus kembali dihidupkan, hanya kita sebagai anak bangsa yang mampu mengkader ulang semangat perjuangan Islam-ilmiah tersebut. (Mc-V)